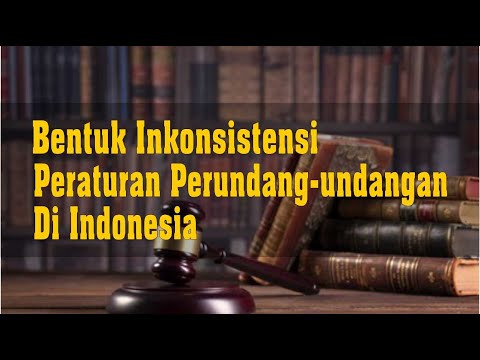Dalam labirinnya aturan perundang-undangan Indonesia, kerap kita temukan benang kusut problematika yg tak hanya membingungkan masyarakat awam, tetapi juga para praktisi hukum. Fenomena inkonsistensi hukum menjadi momok dalam tatanan peraturan perundang-undangan negeri ini. Seolah menjadi penyakit kronis yg menahun, inkonsistensi norma hukum hadir dalam berbagai bentuk mulai dari tumpang tindih kewenangan, benturan norma, dan konflik kepentingan dlm berbagai aspek pelaksanaan peraturan1. Betapa sering kita merasa bingung ketika satu aturan berkata A sementara aturan lain menyatakan B terhadap substansi yang serupa? Bagaimana bisa kita mengharapkan sistem hukum yang efisien jika pondasi utamanya saja tidak konsisten? Ini yg saya dan mungkin Anda juga rasakan saat berurusan dengan aspek hukum tertentu di negri kita.
Dibawah kacamata legal expertise, inknsistensi norma hukum sejatinya menunjukkan belum terintegrasinya sistem hukum nasional secara utuh. Koch dan Rusmann, sebagimana diketahui, membedakan tiga kasus ketidakjelasan hukum dlm sistem normatif—yaitu ambiguity (ambiguitas), inconsistency (inkonsistensi), dan vagueness (kesamaran)2. Tentang hal ini, menarik sekali untuk menyimak bagaimana proses pembentukn peraturan perundang-undangan ternya mengalami beberapa kendala substantif. Aturan yang dibuat dengan tergesa-gesa atau "kejar tayang" sebagaimana diutarakan oleh banyak ahli, sering kali menjadi salah satu biang keladi munculnya inkonsistensi vertikal maupun horizontal dalam tata norma hukum3. Kita juga harus fokus memahami apa sebnernya yang dimaksud dg inkonsistensi hukum ini? Di mana letak permasalahannya? Mengapa hal ini trus menerus terjadi di negara yg mengagung-agungkan kepastian hukum seperti Indonesia?
Konsep dan Definisi Inkonsistensi Hukum
Inkonsistensi hukum, dalam pemahaman dasarnya, merujuk pada kondisi dimana terdapat pertentangan antar norma dalam sistem hukum yang berlaku. Mathias Klatt mengenalkan istilah "legal indeterminacy" untuk menggambarkan kondisi ketika hukum tidak dapat ditentukan secara tepat—suatu manifestasi dari problematika yuridis yang cukup pelik2. Dalam prakteknya, seperti kata teman saya yg ahli dlm bidang ini, inkonsistensi bisa hadir dlm beberapa wujud: kekosongan hukum (ketika tidak ada regulasi yang mengatur), ketidakharmonisan atau tumpang tindih (ketika ada banyak aturan bertentangan), serta prtaturan yang ada tapi tidak memadai (ada tapi tak memenuhi kebutuhan)1. Hal-hal inilah yang sering membuat para mahasiswa dan praktisi hukum pusing tujuh keliling. Coba kita bayangkn masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang pendidkan hukum—tentu kebingungannya berlipat ganda!
Konsep ini diperluas oleh L.M. Gandhi yang mengidentifikasi delapan faktor penyebab munculnya disharmoni atau inkonsistensi dlm praktik hukum di Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan3. Bagi Sidharta, terjadinya inkonsistensi hukum merupakan suatu hal yang umum yaitu adanya benturan norma yang kemudian saling menderogasikan3. Para siua sedang melukis gambaran bahwa inkonsistensi norma dalam sistem hukum kita lebih merupakan sesuatu yang wajar daripada pengecualian. Apakah ini normal? Bisakah kita terima begitu sja? Dalam legal framework modern, konsistensi harusnya menjadi fondasi utama dari sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian. Tumpang tindih peraturan yang membingungkan masyarakat justru melanggengkan ketidakpastian hukum. Maka yg jadi pertanyaan adalah: siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara mengatasinya?
Bentuk Inkonsistensi dalam Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—sebagai payung hukum dalam pembentukan regulasi—rupanya juga tidak luput dari fenomena inkonsistensi norma. Inkonsistensi norma trkait naskah akademik dalam UU tersebut terlihat pada beberapa pasal. Di bagian ketentuan umum pasal 1 ayat 11, bagian undang-undang perencanaan pasal 19 ayat 3, dan bagian perencanaan peraturan daerah provinsi pasal 33 ayat 3 terlihat konsisten. Namun anehnya, bagian penysunan peraturan daerah provinsi pasal 56 ayat 2 menunjukkan ketidakkonsistenan1. Ini menjadi ilustrasi nyata betapa peraturan tentang cara membuat peraturan pun tak lepas dari masalah inkonsistensi internal. Pertanyaannya adalah: bagaimana mungkin kita berharap produk hukum yang dihasilkan bisa konsisten jika pedoman pembentukannya saja mengandung inkonsistensi? Apakah ini tidak seperti membangun rumah kokoh di atas fondasi pasir?
Inkonsistensi Penggunaan Frasa Hukum
Inkonsistnsi hukum terlihat jelas pada penggunaan frasa "dan/atau" dalam konteks naskah akademik pada UU No. 12 Tahun 2011. Penggunaan frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan status naskah akademik apakah wajib ataw tidak dalam pembuatan peraturan daerah1. Kekaburan norma semacam ini tentu saja menjadi celah hukum yang mengacaukan implementasi di lapangan. Coba anda bayangkan, jika para pembuat kebijakan di daerah memiliki persepsi berbeda tentang statusnya naskah akademik, bagaimana mungkin kualitas peraturan daerah bisa terjamin? Saya sering mengamati bagaimana ketidakjelasan semacam ini akhirnya memaksa pihak pelaksana kebijakan memilih interpretasi yang paling menguntungkan, bukan yang paling benar. Ini jelas bertentangan dgn semangat transparansi dan akuntabilitas hukum.
Contoh lain inkonsistensi norma terlihat pada penggunaan frasa "mutatis mutandis" yang tidak sesuai dengan bahasa yang biasanya digunakan dalam undang-undang dan tidak ada definisi khusus dalam ketentuan umum1. Ungkapan ini muncul pertama kali pada UU No. 12 tahun 2011 pasal 31 tentang perencanaan Peraturan Presiden, yang kemudian berlaku juga pada peraturan provinsi hingga peraturan kabupaten kota1. Penggunaan istilah latin yg tiba-tiba muncul tanpa penjelasan memadai tentu membingungkan bagi para pembuat kebijakan di daerah, terlebih yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum formal. Bukankah seharusnya peraturan perundang-undangan dibuat untuk dipahami semua pihak, bukan hanya kelompok tertentu? Lalu mengapa masih digunakn istilah yang berpotensi membingungkan?
Inkonsistensi Vertikal dan Horizontal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki struktur yang jelas dengan UUD 1945 sbg norma tertinggi, diikuti Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota4. Inkonsistensi vertikal terjadi ketika peraturan yang lebih rendah bertentangan dgn peraturan yang lebih tinggi hierarkinya3. Kasus nyata terlihat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan Pasal 150 Ayat (4) yang menyatakan "Kepala desa hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024", menciptakan inkonsistensi norma dgn mengurangi masa jabatan dari 6 tahun menjadi 5 tahun4. Ini jelas bertentangan dengan asas lex superior derogate legi inferiori yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi4. Saya perhatikan Perda seringkali menjadi sumber inkonsistensi hukum karena posisinya sebagai peraturan terendah dalam hierarki perundang-undangan4.
Inkonsistensi horizontal terjadi ketika terdapat pertentangan antara peraturan yang setingkat. Contohnya adalah pertentangan antara UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya pada pasal 261. Para tamu-tamu legislatif sebenarnya sudah menyadari hal ini, namun masih blum ada upaya sistematis utk menyelesaikannya. Kondisi seperti ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan para penegak hukum dalam menentukan aturan mana yang harus diikuti. Jika kita pikirkan lebih jauh, kondisi ini potensial menciptakan ketidakadilan karena penerapan hukum menjadi tidak seragam. Anda bisa melihat bagaimana penegakan hukum terhadap kasus serupa kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena perbedaan tafsir akibat inkonsistensi norma ini.
Studi Kasus Inkonsistensi Hukum di Indonesia
Inkonsistensi dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama
Salah satu contoh klasik inkonsistensi norma dalam sistem hukum Indonesia terlihat pada pengaturan perkawinan beda agama. Keberadaan pasal dlm UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan adanya inkonsistensi norma dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia5. Secra umum, Kantor Urusan Agama mencatatkan perkawinan bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Namun, inkonsistensi muncul ketika pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan5. Perhatikan seberapa jauh ini berbeda dgn semangat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang cenderung tidak memfasilitasi perkawinan beda agama! Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa ada pasangan yang harus ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan beda agama sementara sebenarnya ada celah hukum di dalam negeri? Inkonsistensi norma seperti inilah yg menjadi penyebabnya.
Inkonsistensi dalam Pengaturan Hak Tanah Ulayat
Kasus inkonsistensi hukum juga terlihat jelas dalam pengaturan hak atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat. Menurut Sumardjono (2021), konsepsi PP No. 18/2021 mengenai pengaturan atau penetapan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) bagi Masyarakat hukum adat tidaklah jelas maksud dan tujuannya3. Pengertian HPL tidak kompatibel dgn hak ulayat, karena hak ulayat kewenangannya melekat/inheren wewenang daripada siapapun, termasuk dari negara3. Penamaan tanah hak ulayat tidak perlu "diberi nama" dengan HPL karena hakikat tanah ulayat berbeda dengan tanah HPL3. Padahal, Pasal 28 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa "Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan"3. Bisa kita lihat dsini bahwa inkonsistensi vertikal antara PP dengan UUPA potensial merugikan masyarakat hukum adat. Kenapa kira lebih memilih memaksakan konsep HPL yang tidak kompatibell dengan konsep hak ulayat yg sudah mengakar dalam tradisi hukum adat kita selama berabad-abad?
Faktor Penyebab Inkonsistensi Hukum
Menurut L.M. Gandhi, terdapat delapan faktor penyebab munculnya disharmoni atau inkonsistensi dalam praktik hukum di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan3. Saya pikir, cepatnya waktu pengerjaan atau yg sering disebut sebagai "kejar tayang" dalam merumuskan suatu peraturan juga menjadi faktor signifikan penyebab inkonsistensi hukum3. Ketika sebuah peraturan perundang-undangan disusun terburu-buru utk memenuhi tenggat waktu politis, seringkali proses kajian dan harmonisasi tidak dilakukan secara memadai. Coba kita bayangkan, kompleksitas sistem hukum modern memerlukan kajian mendalam dan komprehensif, tetapi ketika proses ini dipaksa diselesaikan dalam waktu singkt, hasilnya tentu tidak sempurna.
Faktor lain yg perlu kita pertimbangkan adalah ego sektoral antar lembaga pembentuk peraturan. Dalam mgengatur objek yang sama, sering kali tiap sektor atau kementerian memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Ketika terjadi konflik antar sesama undang-undang, di mana conflict of norm atas suatu pengaturan yang bersifat kewajiban ataw larangan sama-sama diatur terhadap objek yang sama dalam undang-undang sektoral yang berbeda, asas lex special derogate lex generalis tidak dengan mudah diterapkan3. Apakah ini berarti kita membutuhkan mekanisme koordinasi antar sektor yang lebih kuat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya berpendapat demikian. Koordinasi lintas sktoral merupakan kunci untuk mencegah terjadinya inkonsistensi norma.
Dampak Inkonsistensi Hukum
Inkonsistensi norma berpotensi menimbulkan perbedaan persepektif antara masyarakat dan penegak hukum pada suatu aturan yang menjadi norma4. Saya perhatikan bahwa inkonsistensi hukum melemahkan efektivitas sistem hukum karena menciptakan ambiguitas dalam penerapan norma hukum4. Seringkali masyarakat menjadi bingung tentang aturan mana yang harus diikuti, sementara penegak hukum menghadapi dilema dlm menentukan dasar hukum yang tepat. Hal ini pada akhirnya bermuara pada ketidakpastian hukum yang sangat merugikan masyarakat. Bayangkan jika Anda ingin membuka usaha dan dihadapkan pada peraturan yang saling bertentangan—aturan perizinan di tingkat nasional mengatakan A, sementara di tingkat daerah menyebutkan B. Apa yang akan Anda lakukan? Kebingungan semacam inilah yang sering dialami masyarakt akibat inkonsistensi norma hukum.
Dampak lain yang tak kalah serius adalah potensi terjadinya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Ketika terjadi inkonsistensi norma, implementasinya di lapangan cenderung tidak seragam dan sangat tergantung pada interpretasi masing-masing penegak hukum. Ini tentu saja bertentangan dgn prinsip kepastian dan keadilan hukum. Salah satu contoh konkret adalah persoalan yg muncul dalam pengaturan perkawinan beda agama sebagaimana kita bahas sebelumnya. Seharusnya tindakan hukum yang serupa diperlakukan secara sama di mata hukum, namun karena adanya inkonsistensi norma, perlakuannya bisa berbeda-beda tergantung interpretasi hakim atw pejabat pencatatan sipil. Di kota A perkawinan beda agama mungkin difasilitasi melalui penetapan pengadilan, tetapi di kota B mungkin tidak diijinkan sama sekali. Bagaimana Anda melihat ketidakadilan semacam ini?
Upaya Mengatasi Inkonsistensi Hukum
Zainal Arifin telah mengidentifikasi beberapa prinsip penting dalam mengatasi problematika hkum, di antaranya prinsip konsisten, sinkronisasi, dan harmonisasi normatif vertikal/horizontal2. Harmonisasi normatif vertikal merupakan penyelarasan peraturan perundang-undangan dgn peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti undang-undang dengan UUD NRI Tahun 19452. Dalam koteks pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya inkonsistensi norma. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya melibatkan pengkajian yang komprehensif terhadap seluruh peraturan terkait untuk memastikan tidak adanya pertentangan norma. Bagaimana ini bisa dicapai? Salah satu caranya adalah dengan memperkuat peran Kementerian Hukum dan HAM dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama pada tahap perencanaan dan penyusunan.
Berdasarkan adanya inkonsistensi vertikal dalam berbagai ketentuan PP No. 18/2021, misalnya, diharapkan pemerintah dpt menguji ulang kembali substansi-substansi peraturan tersebut3. Uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung inkonsistensi norma menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Baik melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maupun executive review oleh pemerintah terhadap peraturan di bawah undang-undang. Namun, pendekatan ini bersifat reaktif dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Pendekatan yang lebih proaktif adalah memperkuat sistem pengawasan dlm proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan. Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah di masa depan kita memiliki semacam "early warning system" yang dapat mendeteksi potensi inkonsistensi norma sejak tahap awal pembentukan peraturan?
Kesimpulan
Inkonsistensi hukum merupkan problematika serius yang menggerogoti efektivitas sistem hukum di Indonesia. Fenomena ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakharmonisan antar peraturan, tumpang tindih kewenangan, hingga kekaburan norma dalam suatu peraturan. Sebagai negara hukum, inkonsistensi norma merupakan tantangan yg harus segera diatasi untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Dari berbagai pembahasan di atas, kita dpt menyimpulkan bahwa inkonsistensi hukum tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam implementasinya.
Upaya mengatasi inkonsistensi hukum membutuhkan pendekatan komprehensif yng melibatkan pembenahan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses penyusunan peraturan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik scara vertikal maupun horizontal, menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya inkonsistensi norma. Semoga dengan kesadaran dan upaya bersama, sistem hukum Indonesia dapat terbebaskan dari jerat inkonsistensi norma, sehingga cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan dapat terwujud.
Referensi
- Ruang Alfaris 2. (2024). Bentuk Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. YouTube. https://youtu.be/fQ9LqTvnf1Q
- Dewi, D. R. C. (2017). Inconsistency Norm (norma hukum yang tidak konsisten) dalam Peraturan Perkawinan beda Agama: Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maufiroh, Rachman, & Purnaningrum. (2021). Inkonsistensi Vertikal dalam PP No. 18/2021 dan Bentuk Inkonsistensi Hukum.
- Maenia, A. S. (2023). Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Undergraduate Thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Dewi, D. R. C. (2017). Inconsistency Norm (norma hukum yang tidak konsisten) dalam Peraturan Perkawinan beda Agama. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.